SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Bagai ritual, menjelang pertengahan Mei, media sosial dan media massa kembali membicarakan soal tragedi dan kerusuhan Mei 1998.
Saya turut menuliskan pengalaman berada di tengah-tengah tragedi dan kerusuhan, saat saya menjadi mahasiswa tingkat ke 3. Rangkaian kejadian yang berpuncak hingga turunnya Soeharto sangat memengaruhi pemikiran dan pilihan hidup. Saya pun yakin bahwa saya tidak sendiri.
Namun kenyataan berbicara lain, ternyata generasi berikutnya belum tentu mengenal apalagi terpengaruh dengan apa yang terjadi pada Mei 1998. (BACA: Tragedi Mei ’98, hari-hari menuju reformasi)
Dalam berbagai kesempatan berinteraksi dengan generasi yang lahir setelah tahun 1990, kerap kali saya temui bahwa mereka ragu tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu. Suara Ibu Peduli hingga Sjafrie Sjamsoeddin adalah hal yang asing bagi generasi tersebut hingga saat ini. Generasi tersebut adalah generasi yang mungkin tidak pernah mendengar teriakan, “Revolusi, revolusi sampai mati.”
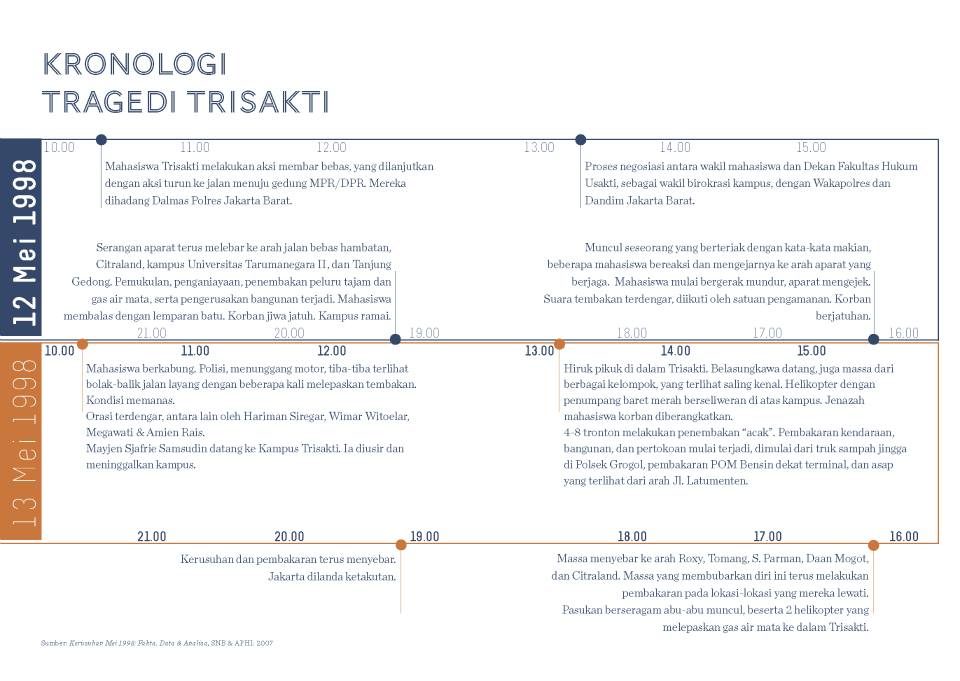
Tahun ini sesungguhnya bukan hanya peringatan 17 tahun Tragedi dan Kerusuhan Mei 1998, tapi juga 50 tahun tragedi 30 September 1965 yang akhirnya mendorong terjadinya rangkaian kejadian dan menyebabkan 500 ribu jiwa lebih (bahkan ada klaim 3 juta jiwa) melayang di Pulau Jawa, Bali, Sumatera hingga Kalimantan.
Kejadian tahun 1965-1966 pun menjadi bahasan tabu di masa Orde Baru. Saya adalah generasi yang hampir setiap tahun pada tanggal 30 September harus menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di TVRI sebagai bagian dari kurikulum sekolah, serta memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada keesokan harinya.
Peran negara sangat besar dalam memutuskan apa yang perlu diingat dan apa yang menjadi sejarah. Orde Baru secara sistematis menanamkan sejarah yang perlu diketahui dalam berbagai struktur pendidikan, entah itu dalam bentuk mata pelajaran, sastra yang perlu dan wajib dikonsumsi, hingga apa yang berhak menjadi memorial.
Seorang cendekiawan sastra Wijaya Herlambang yang meneliti film Pengkhianatan G30S/PKI bahkan menyatakan pemerintah Orde Baru saat itu menggunakan media kebudayaan untuk melegitimasi pembantaian manusia. Generasi yang berulang kali harus menonton film tersebut menganggap bahwa pembantaian terhadap PKI adalah hal yang wajar karena PKI di dalam film itu terlihat sangat kejam.
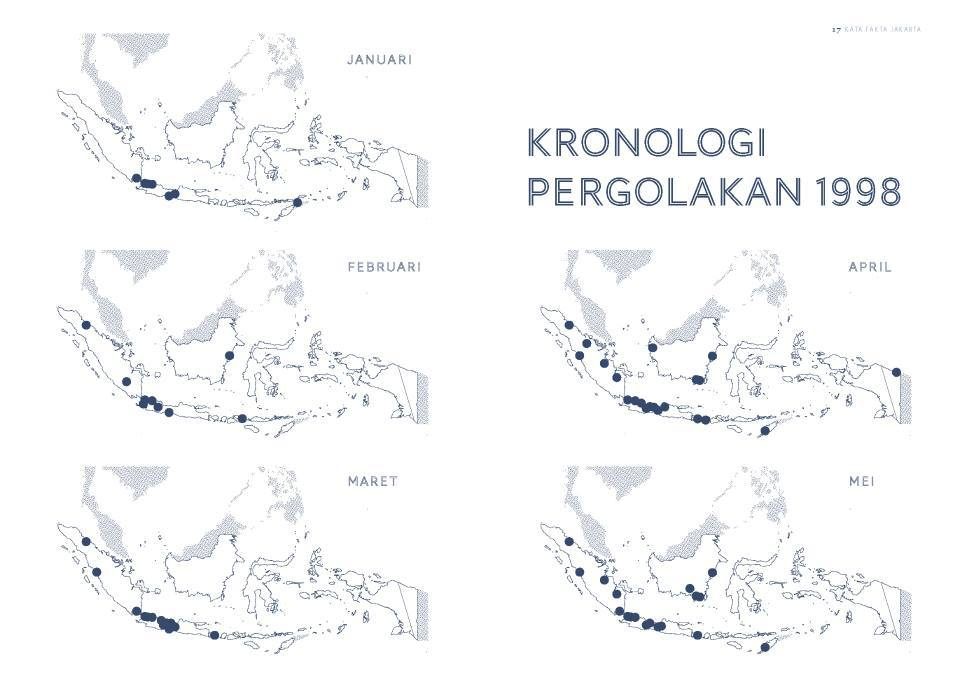
Tidak ada memorial yang terbangun untuk mengenang ratusan ribu hingga jutaan jiwa yang melayang. Yang ada adalah Memorial 7 Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, Jakarta Timur, hingga berbagai taman lalu lintas yang menggunakan nama Ade Irma Nasution.
Memorial yang sesungguhnya memiliki tujuan sama, yaitu untuk menjustifikasi Orde Baru serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan korban melayang yang terjadi sesudahnya.
Beberapa hari lalu, saya mengajukan pertanyaan di laman Facebook saya, mengapa hingga hari ini tidak ada memorial satupun untuk mengenang ratusan ribu hingga jutaan orang yang melayang pasca 1965.
Johanes Widodo, seorang profesor di bidang arsitektur dari National University of Singapore, menyahuti status pertanyaan dengan menyatakan bahwa sebelum membangun memorial, perlu ada riset obyektif berdasarkan data tanpa ada perasaan sentimentil maupun tujuan advokasi — yang hingga saat ini belum pernah dilakukan.
Membangun memorial, terlebih jika dilakukan oleh negara, merupakan sikap politik. Pertanyaan sama juga bisa diterapkan pada mengapa tidak ada memorial atas tragedi dan kerusuhan Mei 1998?
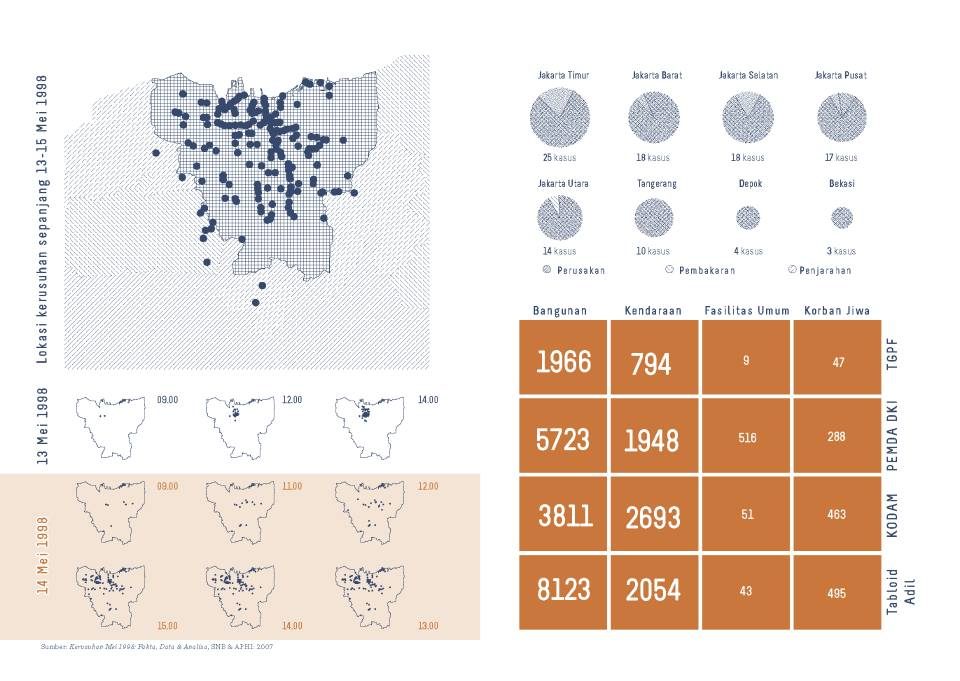
Tahun 2001, atau hampir 14 tahun lalu, ada kelompok arsitek yang terdiri atas Andra Matin, Idris Samad, Sardjono Sani, Ahmad Djuhara, dan Andrew Tirta. Mereka bekerja sama dengan fotografer Agustinus Abimanyu, Seniman Pintu Besar Selatan, serta mahasiswa Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila membangun instalasi berupa intervensi fasad pada bangunan-bangunan yang ditinggal paska Kerusuhan Mei 1998.
Mengutip dari Andrew Tirta, ini adalah upaya arsitektural untuk menunjukkan kepedulian terhadap memori kolektif dan imaji Glodok pasca kerusuhan Mei 1998. Masih teringat dalam benak saya adalah salah satu instalasi yang menggunakan bunga mawar plastik berwarna merah bak darah yang menutupi fasade bangunan yang terbakar. Setelah itu tidak ada upaya untuk mematerialkan tragedi dan kerusuhan Mei 1998 dalam rupa bangunan dan ruang publik.
Memang tahun lalu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, saat itu masih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, meletakkan batu pertama pendirian Prasasti Tragedi Mei 1998. Dan hari ini, 12 Mei 2015, nama 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak tanggal 12 Mei 1998 diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Bogor. Tetapi, kita membutuhkan lebih dari prasasti dan nama jalan. Kita memerlukan wujud yang mampu merekam memori kolektif.
Pembangunan memorial adalah upaya bersama dari negara dan masyarakat memelihara kesadaran. History repeats itself, demikian pepatah yang kerap diucapkan saat membicarakan peristiwa sejarah seperti tragedi dan perang.
Memorial adalah upaya bagaimana agar tragedi dan sejarah buruk tersebut tidak berulang, karena memorial diharapkan dapat menjadi wacana pembelajaran bersama yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Memorial adalah hutang generasi sekarang kepada generasi mendatang, sebagai produk yang memungkinkan dialog antara kenangan dan masa depan.
Jakarta sebagai kota dengan bangunan dan perencanaan kota sebagai artefaknya, sesungguhnya adalah produk gagal Reformasi 1998. Reformasi 1998 yang melahirkan keterbukaan dan demokratisasi dalam berbagai bidang, justru gagal terlihat dalam ruang kota Jakarta.
Kurang dari 5 tahun pasca reformasi, gubernur saat itu, Sutiyoso, malah memagari Taman Monas dengan pagar kokoh setinggi 2.5 meter. Bundaran Hotel Indonesia dipugar sedemikian rupa hingga menyulitkan warga yang hendak menyampaikan aspirasi.
Ketakutan yang muncul pasca tragedi Mei 1998 malah makin menyuburkan gated-community serta upaya privatisasi jalan-jalan publik lewat pembangunan portal-portal yang marak di perumahan. Sutiyoso dan sebagian warga Jakarta memang belajar dari sejarah, namun mereka secara selektif memilih pembelajaran yang justru mengedepankan rasa takut dan otoritas tanpa memungkinkan terjadinya dialog.
Harapan kini ada pada pemerintah baru, yang April silam mengeluarkan komitmen untuk mengusut 2 tragedi pelanggaran HAM di atas. Harapan besar agar ada riset obyektif bersama, seperti yang diungkapkan oleh Johanes Widodo di atas, agar menjadi momentum pembelajaran bersama dan dialog.
Sejarah, dan bagaimana bangsa dan negara menyikapi sejarah, adalah faktor yang membentuk identitas bangsa dan generasi di masa depan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan belajar pada tragedi sebelumnya atau sebaliknya? —Rappler.com

Elisa Sutanudjaja adalah seorang Eisenhower fellow, editor Kata Fakta Jakarta, dan co-founder rujak.org. Ia juga pengupaya sosial, pewarta ‘open data’, dan warga kota Jakarta. Follow Twitter-nya di @elisa_jkt
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.